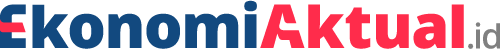JAKARTA – Sebanyak 25 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat sipil menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap rencana investasi perusahaan otomotif global Stellantis di sektor pengolahan nikel Indonesia. Melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Chairman Stellantis N.V, John Elkann di Belanda, mereka menyoroti risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM), perusakan lingkungan, serta ancaman terhadap masyarakat adat yang melekat dalam industri pertambangan nikel nasional.
Surat tersebut menyoroti rencana kerja sama Stellantis dengan PT Vale Indonesia dan Huayou Cobalt untuk membangun fasilitas pengolahan nikel, yang diklaim belum mencakup jaminan perlindungan sosial dan ekologis secara menyeluruh.
“Kami menulis surat ini untuk menyampaikan kekhawatiran serius bahwa rencana investasi Stellantis dalam fasilitas pengolahan nikel bersama Vale Indonesia dan Huayou Cobalt apabila tanpa perlindungan yang memadai, dapat membahayakan masyarakat adat, komunitas lokal, pekerja, dan lingkungan hidup,” tulis koalisi LSM, dalam surat yang dipublikasikan.
Risiko Sistemik di Industri Nikel Nasional
Kelompok masyarakat sipil tersebut mengingatkan bahwa Stellantis, sebagai pemain besar di pasar kendaraan listrik (EV) global, termasuk di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap kehancuran ekologis dan pelanggaran hak asasi.
Dalam suratnya, mereka juga menyinggung kewajiban Stellantis untuk mematuhi Regulasi Baterai Uni Eropa yang akan berlaku mulai 2025, yang menuntut transparansi dan uji tuntas terhadap seluruh rantai pasok bahan baku, termasuk nikel.
Beberapa temuan yang dipaparkan dalam surat tersebut antara lain adalah kerusakan Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara akibat rantai pasok nikel, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga riset Satya Bumi (2024). Penambangan nikel di wilayah tersebut disebut telah mengganggu kehidupan suku Bajau, kelompok nomaden laut terakhir di dunia, bahkan menyebabkan kematian dan perubahan gaya hidup mereka.
Selain itu, laporan keberlanjutan (CSR) Stellantis tahun 2023 juga mencantumkan bahwa bahan baku baterai mereka berasal dari lokasi tambang di Indonesia yang terindikasi memiliki konflik lahan.
Ancaman terhadap Masyarakat Adat dan Kerusakan Lingkungan
LSM juga mengungkapkan keterlibatan Stellantis dalam proyek bersama Samsung SDI untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Amerika Utara, dengan kapasitas produksi awal 34 GWh per tahun. Namun, Samsung SDI juga disebut menerima pasokan nikel dari Indonesia, termasuk dari kawasan industri Morowali Industrial Park (IMIP) yang terkenal kontroversial.
Di sisi lain, perusahaan tambang seperti Weda Bay Nickel di Maluku Utara, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan Prancis Eramet—mitra Stellantis—disebut turut menimbulkan ancaman genosida terhadap komunitas adat Hongana Manyawa yang hidup terisolasi.
“Perusahaan tambang yang merambah tanah milik masyarakat lokal telah memicu kriminalisasi terhadap pembela lingkungan yang mempertahankan hak atas tanah mereka,” tulis koalisi masyarakat sipil.
Tragedi ledakan di fasilitas pengolahan nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali pada Desember 2023, yang menewaskan 13 orang dan melukai 46 lainnya, juga menjadi sorotan. Dalam periode 2015–2022, setidaknya tercatat 47 pekerja meninggal dunia dan 76 lainnya mengalami luka-luka di berbagai lokasi tambang dan smelter nikel di Indonesia.
Emisi Tinggi dan Ancaman Perubahan Iklim
Proses High Pressure Acid Leach (HPAL) yang digunakan untuk mengekstrak nikel dari bijih laterit di Indonesia turut disebut menyisakan limbah tailing berbahaya. Limbah ini mencemari laut dan saluran air, serta memaksa relokasi komunitas lokal.
Lebih parah lagi, operasi pengolahan nikel saat ini masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU). IMIP dan kawasan industri Weda Bay diperkirakan akan memiliki kapasitas listrik 5 gigawatt (GW) dari PLTU captive, setara dengan kapasitas seluruh Pakistan. Ini menempatkan Indonesia di jalur menjadi salah satu negara dengan tingkat emisi karbon tertinggi di dunia—sebuah ironi bagi industri kendaraan listrik yang seharusnya ramah lingkungan.
Desakan Transparansi dan Reformasi Rantai Pasok
Sebagai penutup, 25 LSM tersebut mendesak Stellantis untuk meninjau ulang rencana investasinya di sektor nikel Indonesia dan memastikan setiap keterlibatannya tidak mengorbankan ekosistem, iklim, serta masyarakat adat.
“Sebagai produsen EV besar yang berencana berinvestasi di Indonesia, Stellantis memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa nikel yang digunakan dalam rantai pasokan kendaraan listriknya di Eropa, Cina, Inggris, dan AS bebas dari pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia semacam ini,” tegas mereka.
Mereka juga mendesak agar Stellantis mempublikasikan data lengkap mengenai rantai pasok mineral, termasuk lokasi geografis tambang, pengolah bahan baku, audit pihak ketiga, laporan pengaduan masyarakat, hingga dampak terhadap keanekaragaman hayati, khususnya deforestasi akibat tambang.
Sementara itu, Stellantis saat ini diketahui masih dalam tahap pembicaraan dengan PT Vale Indonesia untuk mengembangkan smelter HPAL dan juga melakukan dialog dengan Huayou Cobalt. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari perusahaan otomotif tersebut menanggapi desakan dari koalisi masyarakat sipil.