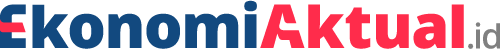JAKARTA – Pemerintah Indonesia kini memasuki babak baru dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan mengukuhkan peran negara bukan lagi sekadar regulator, melainkan pemilik aktif korporasi yang bersaing di pasar bebas. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Transformasi ini membawa dampak signifikan terhadap struktur keuangan negara, khususnya dalam hal keterlibatan fiskal. Aset yang dimasukkan ke dalam BUMN kini dipandang sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dan diperlakukan sebagai milik korporasi, bukan sebagai bagian dari keuangan negara murni yang tunduk sepenuhnya pada logika distribusi sosial.
Arah Baru BUMN: Penciptaan Nilai dan Return on Investment
Berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU No. 1 Tahun 2025, negara tetap dapat menugaskan BUMN untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Namun, hubungan antara kepemilikan negara atas aset BUMN kini difokuskan pada penciptaan nilai dan pengembalian investasi, bukan pada intervensi fiskal langsung.
UU ini memperkuat prinsip bahwa kekayaan negara yang ditanamkan di BUMN bukan lagi bagian dari APBN, melainkan dikelola secara profesional berdasarkan prinsip bisnis dan tata kelola korporasi yang baik.
“Transformasi ini bukan hanya soal struktur hukum, tapi juga mencerminkan pergeseran ideologi negara dalam mengelola aset publik. Negara kini bertindak sebagai pemegang saham aktif, bukan manajer anggaran,” terang pengamat kebijakan publik dalam diskusi refleksi keuangan negara pasca disahkannya UU tersebut.
Dari Sosial Ekonomi ke Logika Bisnis
Perubahan ini menandai pergeseran filosofi besar dari pendekatan sosial-ekonomi menuju logika komersial. Negara tidak lagi terlibat langsung dalam operasional pembiayaan BUMN melalui anggaran, melainkan menyerahkan pengelolaan kepada manajemen profesional untuk menghasilkan profit, efisiensi, dan ekspansi pasar.
Kerangka ini sejalan dengan efficient contracting theory sebagaimana dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam teori tersebut, pemilik korporasi, termasuk negara, harus merancang skema insentif yang mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.
Namun demikian, teori ini juga menyoroti potensi risiko moral hazard, yaitu ketika manajemen BUMN sebagai agen justru bertindak demi kepentingan pribadi yang merugikan negara sebagai prinsipal. Dalam hal ini, Akerlof (1970) mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi agar fungsi sosial BUMN tidak terpinggirkan oleh orientasi profit semata.
“Ketika profit dan valuasi pasar menjadi indikator utama keberhasilan BUMN, kita harus waspada. Risiko asimetri informasi dan moral hazard dapat muncul, dan tanpa tata kelola yang kuat, rakyat bisa saja tidak lagi menjadi prioritas,” tulis Akerlof dalam kajiannya tentang mekanisme pasar dan ketidakpastian kualitas.
Batas Tipis antara Bisnis dan Kepentingan Publik
Transformasi BUMN juga berarti adanya limitasi fiskal negara, tidak hanya dalam aspek teknis, seperti berkurangnya alokasi APBN, tetapi juga dalam dimensi ideologis. Negara mengakui bahwa tidak semua kekayaan publik harus dikelola dengan prinsip distribusi sosial.
Hal ini menjadi refleksi penting: dalam era di mana BUMN didorong menjadi entitas komersial global, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah rakyat sebagai pemilik sejati kekayaan negara, atau elite korporasi yang menguasai arah kebijakan dan keputusan bisnis?
Pengawasan publik yang lemah dan absennya akuntabilitas bisa menyebabkan BUMN menjadi tameng baru bagi praktik-praktik eksklusif yang mengaburkan nilai-nilai demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, tata kelola BUMN ke depan tidak hanya harus efisien secara bisnis, tapi juga adil secara sosial.
“Era kebangkitan BUMN bukan hanya soal ekspansi pasar dan peningkatan laba. Ini soal bagaimana negara menyeimbangkan antara logika bisnis dan tanggung jawab publik. Tanpa transparansi, transformasi ini bisa menjadi jebakan baru,” tegas pakar ekonomi publik dalam forum akademik pekan lalu.
Jalan ke Depan: Akuntabilitas dan Tata Kelola Adaptif
Tantangan utama ke depan adalah menjaga akuntabilitas dan transparansi di tengah orientasi bisnis BUMN. Negara, sebagai pemilik, harus mampu membangun sistem pengawasan yang efektif, memperkuat regulasi yang adaptif, dan memastikan manajemen BUMN tetap bertanggung jawab kepada rakyat.
Reformasi ini menjadi kesempatan emas untuk menjadikan BUMN sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, bukan sekadar alat ekspansi korporasi negara.
Dengan batas fiskal yang semakin ketat, tata kelola korporasi harus diperkuat agar tidak terjadi deviasi tujuan antara kepentingan publik dan ambisi bisnis. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan ketimpangan, keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial menjadi agenda utama dalam mengelola BUMN masa depan.